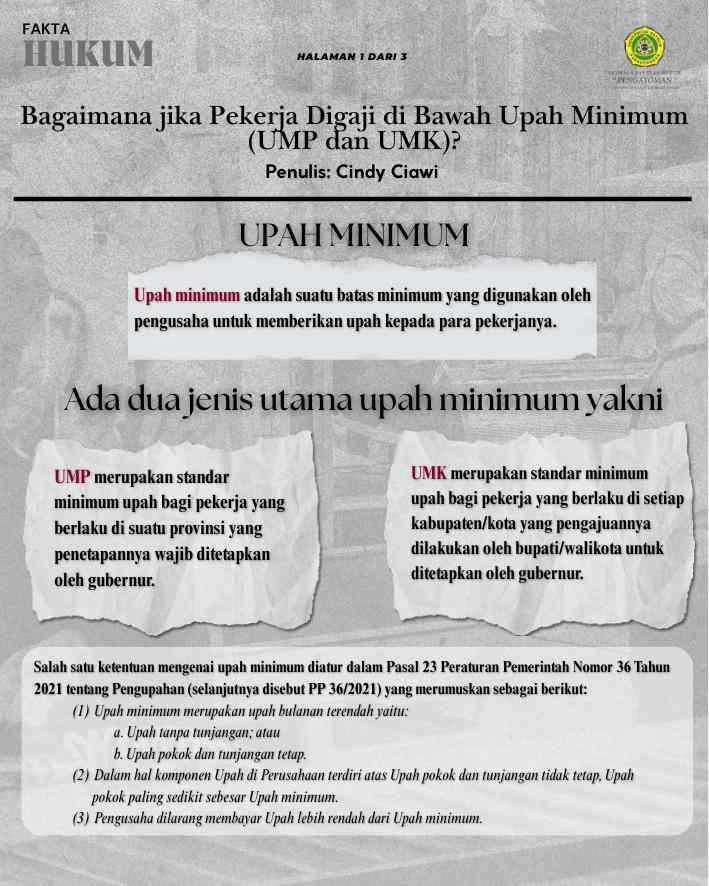
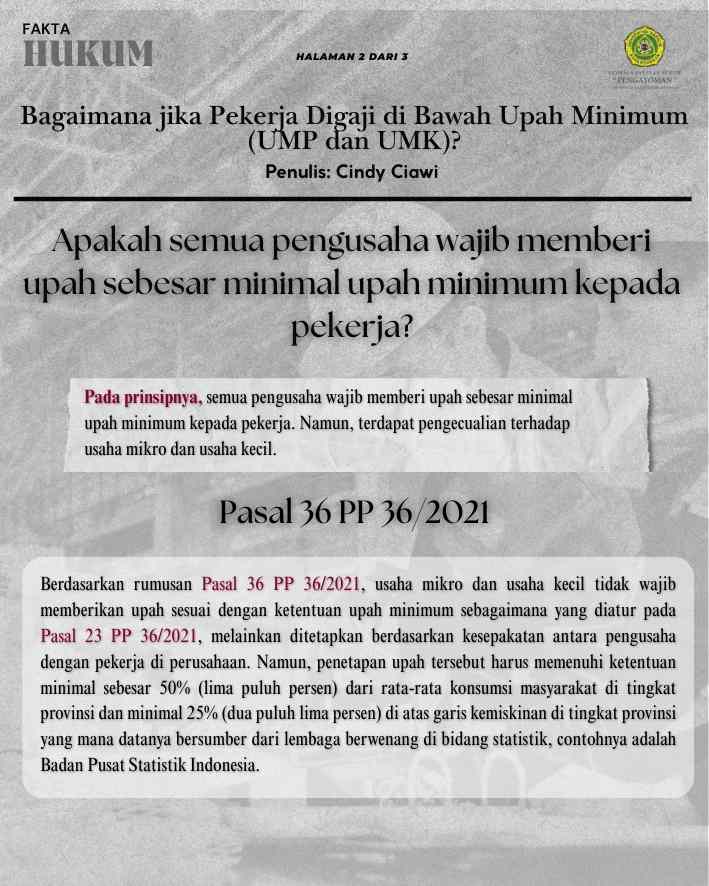
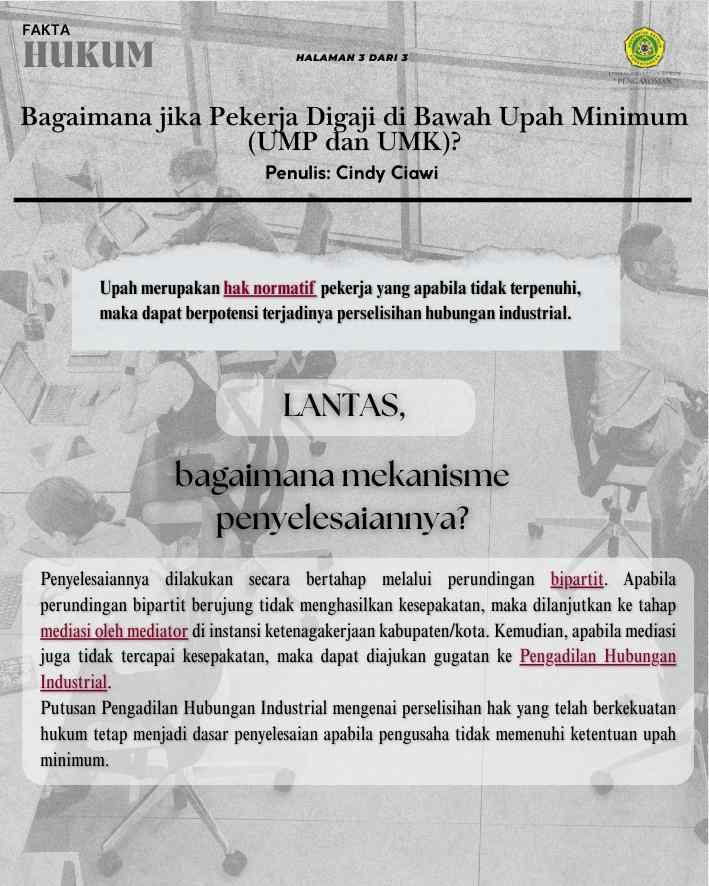
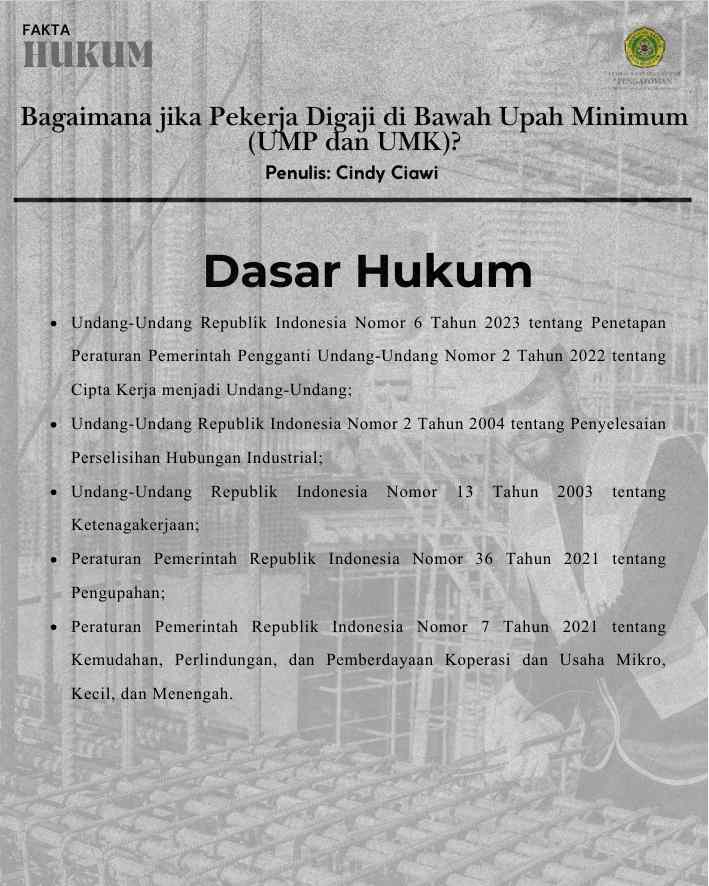
Penulis: Cindy Ciawi
Dalam rangka upaya mewujudkan hak pekerja atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan upah minimum.[1] Ketika berbicara mengenai upah minimum bagi pekerja, pada dasarnya terdapat banyak istilah yang perlu dipahami. Hal ini dikarenakan terdapat istilah-istilah yang jika tidak dipahami maka berpotensi menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Istilah-istilah tersebut di antaranya adalah Upah Minimum Provinsi (selanjutnya disebut UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut UMK). Melalui artikel ini, Penulis akan menjabarkan pemaknaan dari UMP dan UMK, serta bagaimana mekanisme penyelesaian apabila UMP dan UMK tidak terpenuhi.
Upah minimum adalah suatu batas terendah yang digunakan oleh pengusaha untuk memberikan upah kepada para pekerjanya.[2] Ada dua jenis utama upah minimum yakni UMP dan UMK. Saat ini, UMP dan UMK diatur dalam Pasal 81 angka 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Berdasarkan Pasal 81 angka 28 UU Cipta Kerja, UMP merupakan standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di suatu provinsi yang penetapannya wajib ditetapkan oleh gubernur. Di sisi lain, UMK merupakan standar minimum upah bagi pekerja yang berlaku di setiap kabupaten/kota yang pengajuannya dilakukan oleh bupati/walikota untuk ditetapkan oleh gubernur. Gubernur dapat menetapkan UMK dalam hal hasil penghitungan UMK lebih tinggi dari UMP.
Lebih lanjut, upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (selanjutnya disebut PP 36/2021). Salah satu ketentuannya diatur dalam Pasal 23 PP 36/2021 merumuskan sebagai berikut:
“(1) Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yaitu:
a. Upah tanpa tunjangan; atau
b. Upah pokok dan tunjangan tetap.
(2) Dalam hal komponen Upah di Perusahaan terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tidak tetap, Upah pokok paling sedikit sebesar Upah minimum.
(3) Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum.”
Upah tanpa tunjangan yang dimaksud dalam rumusan pasal di atas adalah upah yang tidak disertai dengan komponen lain seperti tunjangan tetap ataupun tunjangan tidak tetap. Contohnya adalah seorang pekerja yang menerima gaji bersih sebesar Rp5.000.000,00 per bulan, di mana nominal tersebut adalah jumlah utuh yang diberikan tanpa komponen tambahan lainnya. Di sisi lain, upah pokok dan tunjangan tetap adalah upah pokok yang disertai tunjangan tetap (misalnya tunjangan hari tua, tunjangan kesehatan, dll). Besaran upah pokok adalah minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.[3] Contohnya adalah seorang pekerja menerima upah bulanan sebesar Rp5.000.000,00 dengan komponen yang terdiri dari upah pokok Rp3.750.000,00 dan tunjangan tetap Rp1.250.000,00. Kemudian, jika upah di suatu perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap (seperti uang makan, uang kehadiran, dll), maka upah pokok minimal adalah sebesar upah minimum. Dengan demikian, pengusaha tetap tidak diperkenankan memberikan upah di bawah batas minimum yang ditetapkan, baik berdasarkan UMP maupun UMK, karena ketentuan ini berlaku sebagai standar upah terendah yang wajib dipenuhi di setiap daerah. Misalnya, UMP Jawa Barat pada tahun 2025 adalah Rp2.191.238,00. Maka, pengusaha di Provinsi Jawa Barat tidak boleh memberi upah di bawah UMP Jawa Barat tersebut. Hal ini berlaku bagi UMP dan UMK di seluruh daerah sebagai upah minimum.
Pertanyaannya, apakah semua pengusaha wajib memberi upah sebesar minimal upah minimum kepada pekerja? Pada prinsipnya, semua pengusaha wajib memberi upah sebesar minimal upah minimum kepada pekerja. Namun, terdapat pengecualian terhadap usaha mikro dan usaha kecil. Pengertian dan kriteria dari usaha mikro dan kecil terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut PP 7/2021). Usaha mikro adalah kegiatan usaha yang dijalankan secara produktif oleh individu dan/atau badan usaha yang dimiliki oleh perorangan, yang sesuai dengan kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam PP 7/2021.[4] Kriteria modal dan hasil penjualan tahunan usaha mikro dan kecil terdapat pada Pasal 35 ayat (3) dan (5) PP 7/2021 yang menjelaskan bahwa usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan maksimal Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Selanjutnya, usaha kecil adalah usaha ekonomi yang bersifat produktif dan dijalankan oleh individu atau badan usaha, yang tidak merupakan anak atau cabang dari perusahaan lain yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, serta memenuhi kriteria sebagai usaha kecil sesuai dengan ketentuan dalam PP 7/2021. Kriteria usaha kecil yang dimaksud adalah usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan maksimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan maksimal Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
Pengecualian pemberian upah minimum oleh usaha mikro dan kecil diatur dalam Pasal 36 PP 36/2021 yang merumuskan sebagai berikut:
“(1) Ketentuan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 35 dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil.
(2) Upah pada usaha mikro dan usaha kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/ Buruh di Perusahaan dengan ketentuan:
a. paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi; dan
b. nilai Upah yang disepakati paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi.
(3) Rata-rata konsumsi masyarakat dan garis kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.”
Dengan melihat rumusan pasal di atas, Penulis menyimpulkan bahwa usaha mikro dan usaha kecil tidak wajib memberikan upah sesuai dengan ketentuan upah minimum sebagaimana yang diatur pada Pasal 23 PP 36/2021, melainkan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja di perusahaan. Namun, penetapan upah tersebut harus memenuhi ketentuan minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi dan minimal 25% (dua puluh lima persen) di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi yang mana datanya bersumber dari lembaga berwenang di bidang statistik, contohnya adalah Badan Pusat Statistik Indonesia.
Berbicara mengenai upah, upah merupakan hak pekerja yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja.[5] Upah merupakan hak normatif pekerja[6] yang apabila tidak terpenuhi, maka dapat berpotensi terjadinya perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.[7] Oleh karena upah termasuk hak pekerja, maka perselisihan antara pengusaha dengan pekerja mengenai upah merupakan perselisihan hubungan industrial. Jadi, apabila perusahaan selain usaha kecil dan mikro memberikan upah kepada pekerja dengan tidak memenuhi ketentuan upah minimum, hal tersebut berpotensi terjadinya perselisihan hak, yang termasuk salah satu jenis perselisihan hubungan industrial.
Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial berbeda-beda sesuai dengan jenis perselisihannya. Berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial, khususnya perselisihan hak, mekanisme penyelesaiannya dilakukan secara bertahap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut UU 2/2004) yakni sebagai berikut. Pertama, penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus diupayakan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit dengan cara musyawarah guna mencapai kesepakatan bersama.[8] Adapun maksud dari perundingan bipartit adalah perundingan yang dilakukan antara pengusaha atau asosiasi pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh, atau antara sesama serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan yang sedang mengalami perselisihan.[9]
Selanjutnya, apabila perundingan bipartit berujung tidak menghasilkan kesepakatan, maka salah satu atau kedua pihak yang berselisih dapat mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan setempat dengan disertai bukti bahwa penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.[10] Lalu, setelah menerima pencatatan dari salah satu atau kedua belah pihak, instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator untuk dilakukan mediasi.[11] Mediasi dalam penyelesaian perselisihan dilakukan oleh mediator yang bertugas pada kantor instansi ketenagakerjaan di setiap kabupaten atau kota.[12] Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. Namun, apabila penyelesaian melalui mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka salah satu pihak berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.[13]
Lebih lanjut, Pengadilan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut PHI) merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum.[14] Dalam hal perselisihan hak, PHI bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus di tingkat pertama.[15] Selanjutnya, gugatan terkait perselisihan hubungan industrial diajukan ke PHI yang berada pada Pengadilan Negeri dengan wilayah hukum yang mencakup lokasi tempat pekerja.[16] Misalnya, seorang pekerja di PT Sejahtera Abadi yang berlokasi di Semarang mengalami perselisihan hak (mendapatkan upah di bawah upah minimum). Dalam hal ini, apabila bipartit dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada PHI pada Pengadilan Negeri Semarang karena pengadilan tersebutlah yang memiliki wilayah hukum yang meliputi tempat pekerja tersebut bekerja.
Kemudian, putusan PHI pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak, termasuk pemberian upah di bawah upah minimum, mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya empat belas hari kerja.[17] Bagi pihak yang hadir, empat belas hari kerja tersebut terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim.[18] Selanjutnya, bagi pihak yang tidak hadir, empat belas hari kerja tersebut terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan.[19]
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa upah minimum yang terdiri dari UMP dan UMK ditetapkan pemerintah sebagai upah bulanan terendah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja, produktivitas, kemajuan perusahaan, dan perkembangan perekonomian. Lebih lanjut, UMP berlaku untuk seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi, sedangkan UMK berlaku di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, baik UMP maupun UMK, kecuali bagi usaha mikro dan usaha kecil yang penetapan upahnya dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan pekerja dengan syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, apabila pengusaha membayar upah di bawah upah minimum, maka timbul perselisihan hak yang termasuk salah satu perselisihan hubungan industrial. Kemudian, penyelesaiannya dilakukan secara bertahap mulai dari perundingan bipartit, mediasi oleh mediator di instansi ketenagakerjaan kabupaten/kota, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Lebih lanjut, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai perselisihan hak yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi dasar penyelesaian apabila pengusaha tidak memenuhi ketentuan upah minimum.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Referensi:
[1] Pasal 81 angka 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
[2] Edi Pang, Mengenal Upah Minimum, https://indonesiabaik.id/infografis/mengenal-upah-minimum (diakses pada 15 September 2025).
[3] Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
[4] Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
[5] Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
[6] Hak normatif pekerja adalah hak dasar yang diberikan kepada pekerja oleh perusahaan atau pengusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
[7] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
[8] Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
[9] Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
[10] Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
[11] Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
[12] Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
[13] Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
[14] Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
[15] Pasal 56 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
[16] Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
[17] Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
[18] Pasal 110 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
[19] Pasal 110 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

![2. [NEW] DESAIN COVER AI (4 x 5 cm) (1)](https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/wp-content/uploads/2025/09/2.-NEW-DESAIN-COVER-AI-4-x-5-cm-1.jpg)

