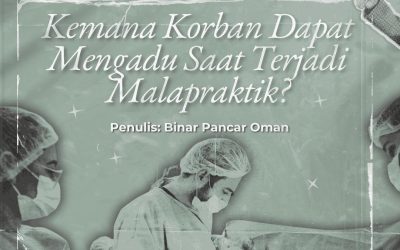Narasumber: Agustinus Pohan, S.H., M.S.
Notulen: Raymond Candela
Sejak lama, telah ada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanggung jawab pidana korporasi, namun penegakannya masih lemah. Peraturan perundang-undangan yang mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dimintakan tanggung jawab tersebut memiliki model yang berbeda-beda satu sama lain. Terdapat model peraturan yang menyatakan bahwa korporasi diakui dan dapat melakukan tindak pidana tetapi tanggung jawab pidananya dibebankan kepada pengurus korporasi. Di lain sisi, terdapat juga model yang menyatakan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia tetapi tanggung jawabnya dibebankan kepada korporasi. Peraturan perundang-undangan tersebut juga menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam penyebutannya seperti korporasi, badan usaha, dan badan hukum. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang lebih jelas, lebih lengkap, dan seragam, maka diperlukan suatu pengaturan yakni KUHP.
Sebelum adanya KUHP baru, terdapat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (selanjutnya disebut PERMA No. 13/2016) yang utamanya mengatur mengenai apa itu tindak pidana korporasi dan bagaimana meminta tanggung jawab pidana pada korporasi. PERMA No. 13/2016 diperlukan karena Undang-Undang yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana korporasi. Perlu diketahui bahwa pengurus tidak melulu adalah pemilik korporasi. Urgensi dari meminta tanggung jawab pidana korporasi adalah soal keadilan. Hal itu dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan yang kemudian tanggung jawabnya hanya dibebankan pada pengurus akan muncul ketidakadilan. Ketidakadilan ini muncul karena pengurus tidak selalu adalah pemilik tetapi pengurus seringkali adalah hanya seorang profesional atau pekerja yang diupah. Permasalahan lainnya adalah ketika sanksi yang besar dijatuhkan kepada pegawai, maka akan muncul ketidakadilan karena kemampuan finansial dari pegawai terbatas. Di sisi lain sanksi yang ringan akan sangat merugikan negara dan masyarakat dalam jumlah besar. . Contohnya, kasus penyuapan oleh pengurus. Perilaku ini memang dilakukan oleh pengurus, namun atas persetujuan dan demi keuntungan korporasi. Korporasi membiarkannya dan menikmati keuntungannya. Oleh karena itu, perubahan perilaku korporasi menjadi kunci pencegahan.
Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum tidak dapat dikatakan sebagai perkembangan, melainkan kebutuhan lama untuk mencapai penegakan hukum adil dan efektif. Perkembangan yang ada terletak pada penyempurnaan aturan agar seimbang dan lebih baik bagi masyarakat. Pemidanaan terhadap korporasi berpotensi memunculkan dampak negatif, maka pengaturannya harus lengkap dan seimbang. Dengan adanya perkembangan yang sekarang, negara dapat menjerat korporasi tanpa menimbulkan dampak-dampak negatif yang meluas dan menimbulkan kerugian. Maka dari itu, diperlukan model pengaturan yang bijaksana berkaitan dengan tanggung jawab pidana pada korporasi.
Pembuktian kesalahan korporasi merupakan salah satu hambatan di masa lalu dalam menjerat korporasi. Hal ini dikarenakan kebingungan dalam menentukan cara membuktikan kesalahan korporasi. Lebih dari itu, muncul pertanyaan mendasar “perlukah kita mensyaratkan adanya kesalahan?” karena asas pidana di Indonesia adalah tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga apakah unsur kesalahan tersebut dapat dikecualikan? Kesalahan diartikan sebagai sikap batin/mens rea tentu yang dimiliki manusia bukan korporasi. Dalam perumusan tindak pidana terdapat sengaja dan kelalaian (alpha). Pada dasarnya, kesengajaan atau alpha hanya dapat dimiliki oleh manusia, karena tidak mungkin korporasi mempunyai kesengajaan. Kesengajaan itu adalah bentuk kesalahan yang dimiliki oleh manusia sebagai naturlijke person. Pada perumusan PERMA No. 13/2016 membahas mengenai kesalahan korporasi dengan mengecualikan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Namun, asas ini mutlak berlaku bagi semua subjek hukum. Solusi yang lebih tepat untuk hukum Indonesia adalah merumuskan kesalahan korporasi, bukan dalam bentuk psikologis, melainkan dalam bentuk kesalahan normatif. Penggunaan kesalahan normatif tidak melihat sikap batin, melainkan berdasarkan norma saja. Sebagai contoh dalam PERMA No. 13/2016 menyatakan apabila keuntungan yang didapatkan dari kejahatan dimanfaatkan oleh korporasi, maka korporasi dikatakan telah melakukan kesalahan.Misalnya, ketika pegawai korporasi melakukan penyuapan dan keuntungannya dinikmati korporasi, maka korporasi telah melakukan kesalahan. Korporasi juga dapat dikatakan salah secara normatif ketika tidak melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana oleh pegawainya. Contohnya, seorang atasan di korporasi harus langsung melaporkan kepada polisi jika ada bawahannya yang melakukan tindak pidana. Dalam KUHP baru, untuk menentukan salah atau tidaknya dilakukan dengan melihat apakah korporasi menerima sebagai kebijakan. Artinya, korporasi memanfaatkan hasil tindak pidana yang dilakukan pegawainya. Di negara lain, korporasi bertanggung jawab sebagai majikan atas tindak pidana yang dilakukan pegawainya. Di Indonesia, hal ini hanya dikenal dalam hukum perdata, bukan hukum pidana. Sementara itu, hukum pidana di Indonesia tidak pernah mengakui korporasi sebagai majikan. KUHP baru memungkinkan penggunaan vicarious liability, namun hanya jika ada Undang-Undang yang secara tegas mengaturnya. Artinya, harus ada peraturan baru yang mengatur korporasi dapat dikenakan vicarious liability.
Pada dasarnya, tindak pidana korporasi secara materiil selalu dilakukan oleh manusia. Akan tetapi, kita perlu membuat kriteria kapan tindak pidana korporasi dikatakan sebagai tindak pidana perorangan, pegawai, pengurus, atau pengurus dan korporasi. Contohnya terjadi perkelahian antara satpam dengan pengunjung di kafe karena mengacaukan kafe tersebut, sehingga satpam tersebut memukul pengunjung tersebut. Dari kasus ini timbul pertanyaan apakah pemukulan tersebut adalah perbuatan satpam saja atau perbuatan korporasi karena satpam sedang melakukan hal tersebut dalam rangka mengamankan kafe yang dimiliki oleh perusahaan. Dahulu pada umumnya yang disebut tindak pidana korporasi harus dilakukan oleh pengurus yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi. Pengurus dalam konteks ini adalah dewan direksi, manajer, dan tergantung pada struktur organisasi perusahaan atau siapapun yang dianggap sebagai personifikasi dari korporasi. Seiring dengan perkembangan waktu, terdapat perumusan baru yang mana pelaku materialnya tidak hanya pengurus tetapi dapat dilakukan oleh pihak lain yang mempunyai hubungan kerja oleh korporasi. Akan tetapi, ada persoalan lain misalnya ketika pegawai yang tidak secara langsung memiliki kontrak dengan perusahaan karena direkrut melalui outsourcing, sehingga terdapat perumusan baru yakni orang-orang yang mempunyai hubungan lain sehingga luas sekali tidak terbatas pada orang yang mempunyai hubungan kerja.Contohnya, perusahaan yang menyewa pengacara untuk mewakilinya di pengadilan. Hubungan ini bukan hubungan kerja, melainkan kontraktual, namun termasuk dalam “hubungan lain”. Contoh lain, perusahaan A menunjuk kontraktor B untuk membongkar gedung. Jika gedung roboh dan menelan korban jiwa, Perusahaan A dapat dipidana karena kontraktor B bertindak atas nama mereka. Perumusan baru ini mendorong perusahaan untuk memilih mitra kerja yang kompeten dan patuh aturan. Jika menggunakan rumusan dalam KUHP baru dan PERMA No. 13/2016, maka tindak pidana tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan Perusahaan A karena kontraktor B melakukan hal tersebut untuk dan atas nama Perusahaan A. Manfaat dari perumusan baru ini adalah perusahaan menjadi terdorong untuk memilih mitra kerja yang kompeten dan patuh aturan. Namun perlu diingat bahwa KUHP baru dan PERMA No. 13/2016 telah memisahkan tindak pidana dan tanggung jawab pidana. Jadi, meskipun perusahaan dianggap melakukan tindak pidana karena hubungan kontraktual, belum tentu perusahaan bertanggung jawab.
KUHP lama tidak memiliki alasan pemaaf untuk korporasi tetapi KUHP baru membuka peluang bagi korporasi untuk mengajukan alasan pemaaf. Pasal tersebut menimbulkan ketidaksesuaian karena tidak mungkin korporasi memiliki jiwa. Penting untuk dipahami bahwa alasan pemaaf bagi korporasi tidak dilihat dari sisi psikologisnya, melainkan dari upaya korporasi dalam mencegah pelanggaran hukum. Misalnya alasan pemaaf karena adanya perintah jabatan dalam hal korporasi diperintahkan oleh suatu penguasa untuk melakukan suatu hal yang melanggar hukum. Contoh lainnya adalah apabila satpam melakukan pembunuhan dalam rangka mengamankan kafe. Ternyata setelah diperiksa perusahaan telah melakukan seleksi dan pelatihan untuk mengendalikan kerusuhan. Ketika perusahaan sudah melakukan hal tersebut berarti perusahaan mempunyai alasan pemaaf karena perusahaan telah melakukan berbagai upaya yang cukup untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum. Dengan demikian dapat diketahui bahwa KUHP baru memberikan peluang bagi korporasi untuk mendapatkan alasan pemaaf.
Pemidanaan korporasi harus didampingi dengan pengaturan dan penegakan hukum yang bijaksana, karena terdapat banyak dampak negatif yang berpotensi muncul dalam memidanakan korporasi. Di negara lain yang sudah lama menerapkan tanggung jawab pidana korporasi, penyelesaian tindak pidana korporasi tidak mutlak melalui proses pengadilan. Misalnya dalam kasus suap Rolls-Royce terkait pengadaan pesawat di Indonesia yang diselesaikan di luar pengadilan dengan sanksi denda. Banyak kasus tindak pidana korporasi diselesaikan di luar pengadilan karena dalam dengan proses penyelesaian di pengadilan, kasus tersebut akan terbuka yang akan dapat membuat korporasi tidak dipercaya lagi oleh masyarakat dan pada akhirnya akan membuat korporasi menjadi bubar. Menurut narasumber, kehadiran pengaturan tanggung jawab korporasi dalam KUHP baru adalah hal yang baik. Akan tetapi, masih terdapat banyak kelemahan dalam KUHP baru terkhususnya mengenai korporasi. Kelemahan-kelemahan yang ada di KUHP baru dapat ditutup dengan menggunakan berbagai tafsir dan putusan.
Tersedia di: